
Dunia baru yang disebut-sebut sebagai dunianya jejaring sosial ini menyimpan sisi gelap. Paling tidak, hal ini yang tersirat dari presentasi James Surowiecki di TED.com.
Dari streaming videonya, James mengingatkan teknologi informasi sudah mengubah konsumen menjadi prosumen. Kekuatan konsumen berkembang, sehingga mitos silent majority itu mulai terkikis.
Sebuah jejaring sosial bukan sekadar produk dari sekian banyak komponen. Lebih dari itu, ini seperti kemunculan fenomena baru. Salah satu karakteristik dasar jejaring adalah, setelah terhubung dan interaksi terbangun, cara pandang Anda ikut terpengaruh oleh orang lain.
Jejaring bisa memiliki semua manfaat berikut: efisiensi dalam penyampaian informasi; akses ke banyak orang; atau mengkoordinasikan kegiatan dengan cara yang sangat baik.
Masalahnya adalah, kelompok hanya menjadi “pintar” ketika orang-orang di dalamnya mandiri. Ini semacam paradoks dari kebijaksanaan massal (Wisdom of Crowds), atau paradoks kecerdasan kolektif; saat kelompok justru butuh kemandirian berpikir anggotanya.
Paradoks dalam jejaring mempersulit orang untuk melakukan kemandirian itu. Dalam jejaring, orang cenderung berperilaku atau mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang dihargai oleh jaringan.
Paradoks ala Surowiecki ini seperti ingin menjelaskan bahwa jejaring sosial hanya optimal bila anggotanya bisa berpikir mandiri. Di sisi lain, berpikir mandiri sangat sulit ketika berada di tengah-tengah jejaring aktif.
Setiap jejaring sosial, entah karena disengaja atau tidak, membentuk cara pandangnya sendiri. Apalagi kalau jejaring itu sudah berlabel cara pandang tertentu.
Misalkan saja Jaringan Islam Liberal (JIL). Sudah jelas cara pandang liberal dalam jejaring itu, kalau Anda tidak suka dengan liberalisme ala mereka, kemungkinan besar Anda tidak akan menikmati berada dalam jaringan itu.
Lalu apa? James Surowiecki menyinggung soal berpikir independen, salah satu elemen dari Wisdom of Crowds, yang ia tulis. Berfokus pada banyak penelitian sosial, dan memberikan banyak sekali anekdot sebagai bukti, Surowiecki mematahkan banyak asumsi tentang bagaimana kelompok bernalar.
Ia juga menjelaskan bagaimana jejaring sosial dapat secara efektif mencapai hasil yang lebih baik dari pada individu. Tapi jangan salah: Grup atau jejaring tidak selalu lebih efisien.
Agar berfungsi dengan baik, “kecerdasan kolektif” tersebut harus memenuhi lima kondisi. Inilah inti dari The Wisdom of Crowds menurut Surowiecki:
- Keanekaragaman: Individu memiliki “pengetahuan pribadi” dan wawasan yang berasal dari berbagai tingkat pengetahuan, pengalaman pribadi, dan cara berpikir mereka tentang dunia. Tidak ada yang bisa menguasai semuanya sendirian. Setiap individu sering kali terlalu percaya diri dan tidak dapat mengkalibrasi penilaiannya sendiri dengan benar.
- Kemandirian: Melindungi kemandirian berpikir sangat penting untuk menciptakan kebijaksanaan. Dengan demikian, pandangan individu dalam kelompok yang beragam sebaiknya dikumpulkan secara terpisah (di luar sesi kelompok) sebelum digabungkan. Metode ini mencegah kesalahan dalam penilaian dan menghindari dampak berkepanjangan karena peniruan pilihan setelah mengamati pilihan orang lain.
- Desentralisasi: Orang yang paling dekat dengan masalah adalah yang paling mungkin memiliki spesialisasi dan pengetahuan tacit yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi kepada mereka yang paling dekat dengan masalah dan paling bertanggung jawab atas hasil umumnya akan menghasilkan solusi yang paling bijaksana. Namun, desentralisasi juga dapat menjebak pengetahuan yang akan menguntungkan entitas yang lebih besar di dalam satu unit. Ini yang harus dihindari.
- Koordinasi: Orang secara inheren pandai mengoordinasikan diri mereka sendiri dan menghasilkan solusi yang hampir optimal meskipun tidak ada komunikasi. Ini berkaitan dengan penalaran kelompok, di samping penalaran individu.
- Agregasi: Ide-ide terbaik dari kelompok yang beragam dan independen tidak berguna tanpa adanya metode agregasi yang tepat. Tanpa agregasi yang tepat, informasi yang dihasilkan oleh orang banyak tidak lebih dari kebisingan. Sering kali agregasi itu sesederhana menghitung jumlah tebakan pribadi pada jumlah jelly bean di dalam toples dan membaginya dengan jumlah tebakan individu untuk mendapatkan tebakan agregat mereka. Dalam kasus lain, metode agregasi yang lebih canggih, seperti teori Bayesian.
Jurus membentuk opini publik
“Suara rakyat adalah suara Tuhan”, katanya. Tetapi suara rakyat bisa juga jadi suara setan. Di balik kearifan jejaring itu, ada sisi gelapnya. Apa yang kita baca di media sosial, media massa, bisa membentuk cara pandang kita. Menguasai media sosial, bisa berarti menguasai opini publik.
Ivan Lanin pernah membahasnya dalam artikel “Kearifan Khalayak” di Politikana. Artikel yang menyoroti fenomena dalam blog terbuka tersebut, menarik untuk ditengok kembali. Saya kutip bagian yang menarik dari sana:
Yang mungkin harus tetap diwaspadai adalah kemungkinan timbulnya riam informasi atau information cascade, yaitu fenomena yang terjadi sewaktu seseorang mengambil pilihan yang serupa dengan orang lain setelah mengamati pilihan orang tersebut.
Meskipun sering dianggap rasional untuk mengikuti pilihan orang lain, apalagi jika itu mewakili suara terbanyak, pilihan itu kadang justru tak berdasar dan bahkan keliru.
Ivan Lanin
“Seseorang mengambil pilihan yang serupa dengan orang lain setelah mengamati pilihan orang tersebut.” Inilah dampak langsung dari pengaruh figur publik di media sosial. Semakin mudah ia menyuarakan pendapatnya—tanpa gatekeeper atau penyeleksi informasi seperti redaksi media—semakin mudah pula ia mendulang dukungan.
Jejaring sosial, mungkin masih eksklusif saat ini. Tapi kalaupun kita bicara “jejaring” model lama, seperti para penonton televisi, efek itu tetap terasa. Para penonton TV berita mungkin mual dan sebal dengan pemberitaan seseorang yang 3-4 bulan lalu disebut sebagai bajingan, tetapi kini digadang sebagai pahlawan. Tapi ketika media berulang-ulang memujanya, rasa mual itu bisa lenyap.
Begitu mudahnya cara pandang (jejaring) media itu membentuk cara pandang khalayak. Begitu mudah pula ia berubah, hingga beredarlah kredo “menolak lupa”—saking mudahnya publik melupakan sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi pelajaran berharga dan tak diulangi lagi.
Hebatnya, ia berlaku nasional, karena mereka tayang hampir di setiap rumah yang memiliki pesawat televisi, dan mampu menerima frekuensi siarannya. Dibanding jangkauan jejaring sosial atau media sosial di internet, televisi masih jauh lebih hebat.
Namun, seperti Surowiecki bilang, meski seribu TV memberitakan sisi kepahlawanan si itu atau kejelekan si anu, independensi dalam memahami situasi, menganalisanya sendiri baru menentukan sikap, sangat dibutuhkan. Keragaman cara pandang dan kemandirian berpikir jadi sangat penting, untuk menciptakan kebijaksanaan bersama. Bila tidak, kita hanya akan terjebak di sisi gelapnya.
Kalau homogenitas cara pandang yang mendominasi media massa (dan media serta jejaring sosial di internet), masyarakat mudah dikelabui, lalu digerakkan dan dimobilisasi untuk kepentingan segelintir kelompok. Bahkan, dipakai untuk menjustifikasi kebijakan publik oleh pemerintah.
Masih ingat Orde Baru yang berusaha ditumbangkan reformasi? Mereka menguasai wacana publik, mengklaim semua satu suara di bawah panji pembangunan. Golkar menjadi simbolnya, sekaligus tunggangan di panggung politik untuk melanggengkan kekuasaan.
“Pak Harto itu masih sehat. Pikirannya juga jelas dan terang. Tinggal bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Presiden. Kalau masyarakat masih menginginkan Pak Harto menjadi Presiden, silakan terus,” kata Sudomo, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, suatu masa pada 1992.
Orde Baru sukses mengeksploitasi sisi gelap jejaring sosial saat itu. Saat itu wacana didominasi oleh satu suara—suara pro-pemerintah. Suara lain dibungkam. Tak ada kemandirian berpikir, tak ada desentralisasi, keaneragaman tinggal jargon yang melekat di kaki Garuda.
Apakah media sosial bisa menjadi penawarnya dengan bereaksi positif atas hal itu? Menawarkan cara pandang yang lebih independen? Bagaimana mengeliminir sisi gelap yang justru bisa kontra produktif terhadap gagasan kearifan itu? Mari sama-sama diskusikan.
Sumber dari TED.com: James Surowiecki: When social media became news | Gambar: handytwitter.com








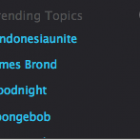

Bener juga. Kadang keputusan saya dipengaruhi oleh apa yg lagi hot dibicarakan. Contoh paling gampang ya, soal film. Ketika di Social media lagi membahas film A -yg katanya bagus- saya juga ikutan nonton. Ternyata — beda dengan selera saya. Tapi yg lebih aneh, ketika ditanya pendapat, saya malah menyetujui pendapat di social media.
It must be stopped!