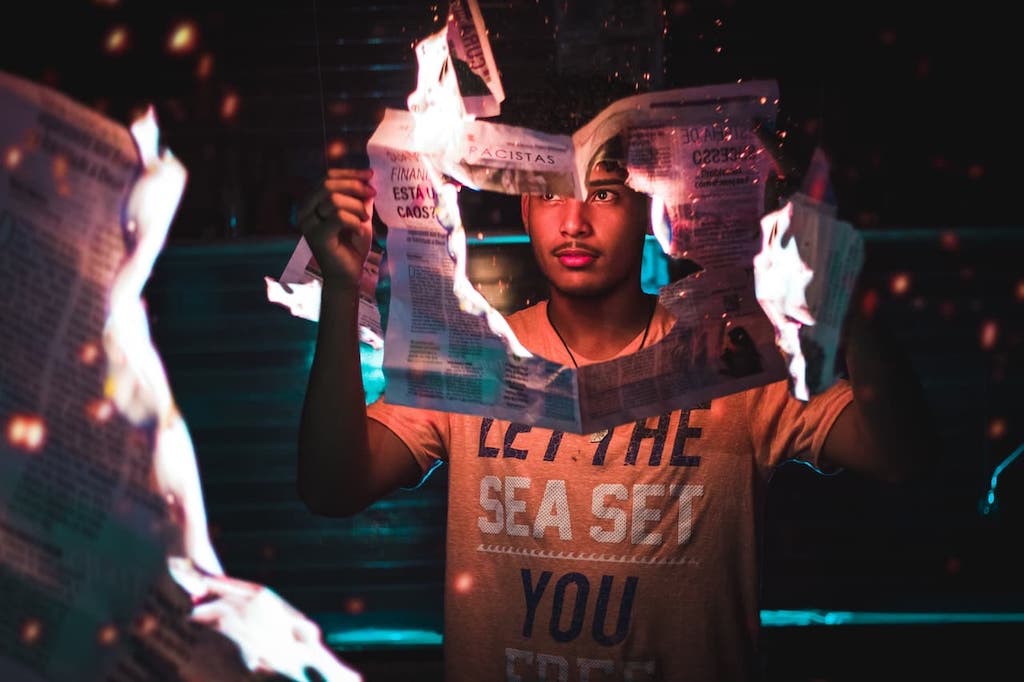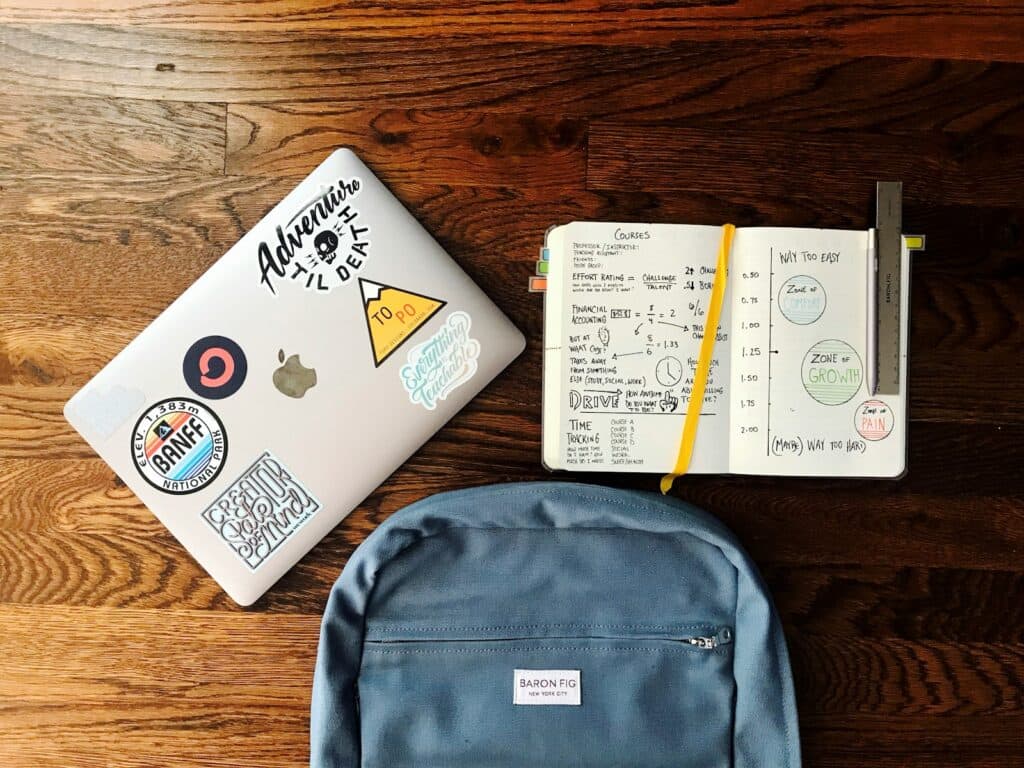
Dalam hitungan tahun, dunia pendidikan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah survei di Inggris pada Desember 2024 menunjukkan angka yang mengejutkan: 92 persen mahasiswa menggunakan alat AI.
Bukan lagi sekadar untuk mencari referensi, tetapi untuk mengerjakan tugas, menulis esai, bahkan membuat kuis. AI seperti ChatGPT telah menjadi “kebiasaan kampus”, sama lazimnya dengan scrolling media sosial.
Pertanyaannya: ketika hampir semua pekerjaan intelektual bisa disimulasikan oleh mesin, apa yang sebenarnya sedang dipelajari mahasiswa? “AI and the Future of Pedagogy” (2025) yang ditulis Dr. Tom Chatfield dan diterbitkan oleh Sage mencoba mencari jawabannya.
White paper yang ditulis oleh filsuf teknologi itu mengangkat dilema fundamental AI dalam pendidikan. Chatfield mengingatkan: “Pembelajaran tidak bisa diotomatisasi atau di-outsource. Belajar adalah proses aktif memperoleh pengetahuan melalui latihan keterampilan yang bermakna.”
Krisis yang Tak Terhindarkan
Bayangkan seorang anak SD yang meminta AI untuk menulis cerita dan menggambar. Tujuan menulis bukan menghasilkan konten lucu untuk dunia, melainkan membantu mereka menjadi warga masyarakat yang literat dan reflektif.
Mahasiswa menulis esai bukan karena dunia butuh lebih banyak esai, tetapi karena proses itulah yang menjadi tujuan—untuk melatih berpikir kritis, menganalisis, dan berargumentasi.
Namun kini, dengan alat AI yang semakin canggih, siswa bisa menyelesaikan tugas konvensional dengan mudah, tanpa benar-benar mengembangkan keterampilan untuk menggunakan AI itu sendiri: kemampuan berpikir kritis, keahlian domain, riset dan verifikasi, serta penalaran analitis.
Sebuah artikel New York Magazine pada Mei 2025 bahkan menggunakan judul provokatif: “Semua Orang Sedang Menyontek di Perguruan Tinggi.”
Lebih ironis lagi, kini ada platform AI yang menawarkan alat untuk memberikan feedback terhadap esai siswa—yang berpotensi menciptakan situasi di mana AI mengevaluasi karya yang juga dibuat oleh AI. Pendidikan berubah menjadi “percakapan antara dua robot”.
Bagaimana Manusia Belajar?
Sebelum membahas solusi teknologi, Chatfield mengingatkan kita untuk kembali ke pertanyaan mendasar: bagaimana manusia sebenarnya belajar? Penelitian kognitif menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika:
- Beban kognitif dikelola dengan baik – Otak manusia mudah kewalahan dengan terlalu banyak informasi atau distraksi. Pembelajaran perlu diselingi, dipraktikkan secara bertahap, dan dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada.
- Metakognisi dikembangkan – Kemampuan untuk “berpikir tentang berpikir sendiri” adalah keterampilan paling penting. Mahasiswa perlu belajar memonitor pemahaman mereka sendiri dan menyesuaikan strategi belajar.
- Pembelajaran bersifat sosial – Debat konstruktif, feedback yang bermakna, dan rasa aman secara emosional adalah bagian integral dari belajar. Ini adalah area di mana AI, meskipun bisa mensimulasikan empati, tidak pernah benar-benar memiliki perspektif atau kepedulian sejati.
AI sebagai Guru atau Ancaman?
Di sinilah paradoks AI dalam pendidikan muncul. Di satu sisi, teknologi seperti Large Language Model (LLM) bisa menjadi “tutor yang tak pernah lelah”, menjelaskan konsep dengan sabar, menyesuaikan tingkat kesulitan secara real-time, dan memberikan latihan yang dipersonalisasi.
Di sisi lain, penggunaan AI yang salah bisa menggerogoti proses belajar itu sendiri. Chatfield mengutip Nicholas Carr: “Mengotomatisasi pembelajaran adalah merusak pembelajaran.” Pernyataan ini mungkin terdengar paradoks di tengah euforia AI. Namun maksudnya sederhana.
Jika AI digunakan untuk menyelesaikan proses belajar (mengerjakan tugas, menulis esai, menghitung soal), maka pembelajaran tidak terjadi. Sebaliknya, jika digunakan mendukung prosesnya (menjelaskan konsep, memberikan feedback, memicu refleksi), maka pembelajaran justru bisa diperkuat.
Perbedaannya terletak pada satu pertanyaan kunci: Apakah mahasiswa masih melakukan kerja kognitif yang bermakna? Berikut contoh penggunaan AI yang tepat (mahasiswa tetap berpikir aktif):
- Menggunakan AI untuk menjelaskan konsep dasar yang sulit dipahami
- Meminta AI menghasilkan berbagai interpretasi teks sastra, lalu mahasiswa menganalisis kelemahannya
- Mahasiswa hukum diminta mencari contoh “halusinasi” AI (informasi palsu yang dihasilkan AI), lalu mengeksplorasi dampaknya
Ini beberapa contoh yang merusak (mahasiswa tidak berpikir, hanya menerima hasil):
- Menggunakan AI untuk menyelesaikan seluruh tugas tanpa refleksi
- Menyerahkan esai hasil AI tanpa pemahaman atas isinya
- Mengandalkan AI sebagai pengganti diskusi dengan teman atau dosen
Dari Pengawasan ke Kolaborasi
Banyak institusi pendidikan merespons krisis ini dengan pendekatan defensif: pengawasan ketat, ujian tertulis tangan, dan perangkat lunak pendeteksi AI. Namun pendekatan ini tidak berkelanjutan. Hampir semua alat deteksi AI tidak dapat diandalkan dan bahkan diskriminatif.
Lebih buruk lagi, pendekatan pengawasan mengubah hubungan antara mahasiswa dan institusi menjadi konflik, bukan kolaborasi. Padahal, sebagian besar mahasiswa sebenarnya ingin belajar menggunakan AI dengan bijak.
Solusi yang lebih baik: mengintegrasikan AI secara transparan dalam proses pembelajaran. Coba pelajari beberapa contoh konkret dari berbagai universitas berikut ini:
- University of Wharton: Mahasiswa menggunakan AI sebagai “mentor virtual” dalam proyek bisnis mereka, tetapi harus menyerahkan log interaksi dengan AI dan refleksi tentang ide mana yang mereka modifikasi atau tolak.
- MIT RAISE Initiative: Mahasiswa diajarkan cara membuat prompt AI yang efektif sebagai bentuk critical thinking, kemudian harus mempertanggungjawabkan pertanyaan dan evaluasi mereka atas jawaban AI.
- Kursus Sastra: Mahasiswa tidak lagi hanya menganalisis teks, tetapi menggunakan AI untuk menghasilkan berbagai interpretasi, lalu membuat argumen tentang keterbatasan interpretasi tersebut.
Studi Kasus: “Cognitive Co-Pilot”
Adapun Chatfield tengah mengembangkan prototipe “cognitive co-pilot” bersama Sage dan City St George’s University of London. Alat ini menggunakan AI untuk:
- Mengajarkan keterampilan berpikir kritis melalui dialog Sokrates
- Melacak progres mahasiswa di setiap bagian silabus
- Menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan respons mahasiswa
- Menghasilkan catatan, ringkasan, dan kuis yang dipersonalisasi
Dalam uji coba dengan mahasiswa, sistem ini mendapat respons positif karena gaya percakapannya yang ringkas, adaptif, dan terstruktur.
Namun yang menarik, mahasiswa juga menyuarakan kekhawatiran: mereka tidak butuh alat untuk menghasilkan konten, tetapi untuk mengelola informasi yang berlebihan dan mendapatkan feedback yang bermakna.
Mengubah Cara Menilai
Mungkin dampak terbesar AI adalah pada sistem penilaian. Ujian dan esai tradisional tidak lagi bisa mengukur apa yang seharusnya mereka ukur.
Ketika mahasiswa punya akses permanen ke sistem yang bisa menghasilkan analisis seketika, pertanyaan kunci bergeser dari “Apa yang kamu tahu?” menjadi “Bagaimana kamu berpikir?”
Pendekatan baru yang muncul:
- Portfolio berbasis proses – Mahasiswa mendokumentasikan perjalanan belajar mereka, termasuk bagaimana mereka menggunakan AI, kesalahan yang mereka buat, dan bagaimana mereka berkembang.
- Penilaian oral – Diskusi langsung dan presentasi menjadi lebih penting karena sulit disimulasikan oleh AI.
- Penilaian berbasis penguasaan (mastery) – Alih-alih nilai tunggal, mahasiswa mendapat kredit ketika menunjukkan pemahaman konsep melalui dialog dan penerapan dalam berbagai konteks.
Etika dan Masa Depan
Pada Mei 2025, ada sebuah kontroversi ketika peneliti dari University of Zurich terungkap diam-diam menguji apakah AI bisa mengubah pandangan orang di forum Reddit.
Hasilnya mengejutkan: bot AI berhasil mengubah pikiran 17-18 persen pengguna, dibanding hanya 3 persen untuk interaksi antar manusia. Tidak ada yang menyadari kehadiran bot tersebut.
Ini mengangkat pertanyaan etis yang mendesak: jika AI bisa begitu persuasif, apa yang menghalangi manipulasi massal?
Namun, neuroscientist David Eagleman menawarkan perspektif berbeda: bot-bot itu berhasil bukan karena memanipulasi emosi, tetapi karena membuat argumen yang lebih baik—rasional, tenang, dan persuasif.
Ini menggambarkan dikotomi inti AI dalam pendidikan: teknologi yang sama bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas berpikir manusia atau untuk memanipulasi dan menggerogotinya.
Bagaimana dengan Pendidikan Indonesia
Berdasarkan paper ini, beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan institusi pendidikan di Indonesia:
1. Jelaskan Ekspektasi dan Melek AI. Ambiguitas kebijakan justru merusak kapasitas mahasiswa dan dosen untuk menggunakan AI dengan percaya diri dan bijak. Buatlah panduan yang jelas kapan AI boleh dan tidak boleh digunakan.
2. Ajarkan Prompt Design sebagai Critical Thinking. Mengajarkan mahasiswa cara membuat pertanyaan yang efektif untuk AI adalah pelajaran tentang presisi dan kejelasan berpikir.
3. Integrasikan Refleksi AI dalam Tugas. Jangan larang AI, tapi minta mahasiswa menjelaskan bagaimana mereka menggunakannya, apa yang mereka pelajari, dan keputusan apa yang mereka buat.
4. Fokus pada Keterampilan yang Komplementer dengan AI. Kembangkan kemampuan yang tidak bisa digantikan mesin: empati, kolaborasi, etika, kreativitas dalam merumuskan masalah, dan kemampuan mensintesis pengetahuan lintas domain.
5. Libatkan Mahasiswa dalam Merancang Rubrik. Sebagian besar mahasiswa ingin belajar menggunakan AI dengan benar. Biarkan mereka ikut mendesain protokol dan rubrik penilaian.
Teknologi Melayani, Bukan Menggantikan
Pada akhirnya, AI dalam pendidikan harus dilihat sebagai alat untuk mengangkat standar kognitif manusia, bukan menggantikannya. Seperti yang ditulis Chatfield: “Dalam era kecerdasan buatan, kesuksesan lebih dari sebelumnya bergantung pada kapasitas yang manusiawi.”
Pendidikan yang baik di era AI bukan tentang melarang atau sepenuhnya merangkul teknologi, tetapi tentang mengajari generasi muda untuk menggunakannya secara kritis, etis, dan reflektif—sambil tetap mengembangkan keterampilan berpikir, berkolaborasi, dan membuat keputusan yang bijak.
AI bukan pengganti guru. Ia adalah konteks baru di mana pembelajaran terjadi—dan pendidik yang paling efektif adalah mereka yang bisa membimbing siswa menavigasi konteks itu dengan kebijaksanaan.
*Photo by Matt Ragland via Unsplash