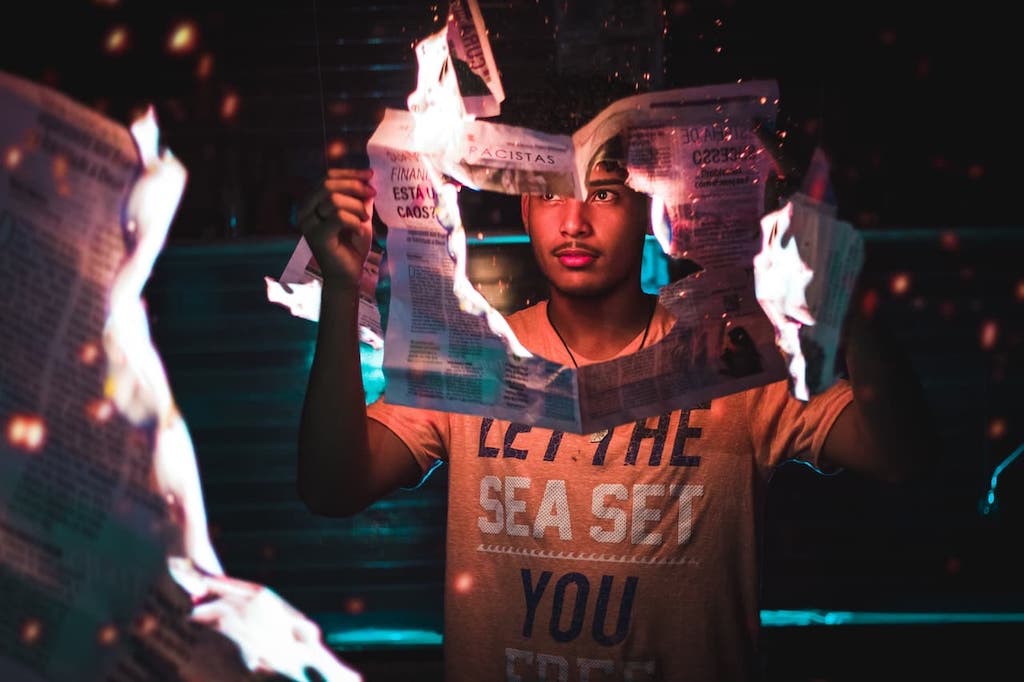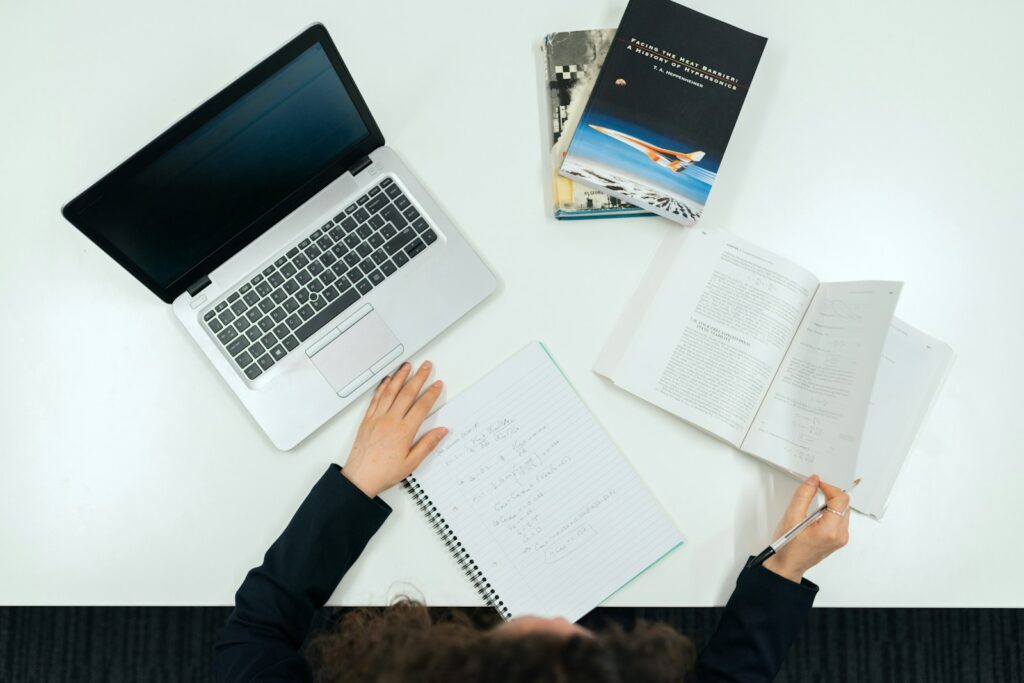
Memperingati Global MIL (Media and Information Literacy) Week 2025, UNESCO merilis dokumen risalah bertajuk Media and Information Literacy for All: Closing the Gaps. Dokumen ini menekankan pentingnya integrasi MIL ke dalam kurikulum pendidikan.
Bayangkan seorang remaja yang membuka ponselnya pagi ini. Dalam sekejap, layar mereka dibanjiri video viral, tips kesehatan yang meragukan, gambar hasil akal imitasi (AI), dan berita breaking news—semuanya bercampur dalam aliran informasi yang sulit dipilah.
Di balik arus deras konten digital ini, tersembunyi risiko nyata: Disinformasi yang merusak opini publik hingga mempengaruhi hasil pemilu, hoaks yang memecah belah masyarakat, serta konten berbahaya yang menggerus kepercayaan dan kesejahteraan mental generasi muda.
Inilah lanskap informasi yang harus dihadapi miliaran orang setiap hari. Dan di tengah kompleksitas ini, sebuah pertanyaan mendesak muncul: apakah sistem pendidikan global telah mempersiapkan warganya dengan keterampilan yang memadai untuk menavigasi realitas digital yang terus berubah?
Laporan penelitian terbaru UNESCO yang diluncurkan pada Oktober 2025 ini memberikan jawaban yang mengkhawatirkan. Meski 171 dari 194 negara anggota UNESCO telah mengakui pentingnya Melek Media dan Informasi (MIL), pengakuan ini belum diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Kesenjangan antara retorika dan realitas ini menciptakan jurang yang berbahaya di era ketika kemampuan berpikir kritis bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan prasyarat untuk bertahan.
Ketika Literasi Digital Disalahpahami sebagai MIL
Indonesia menjadi studi kasus yang menarik—sekaligus mengkhawatirkan—tentang bagaimana kebingungan konseptual dapat menghambat implementasi MIL yang efektif. Meski, laporan UNESCO tidak secaraspesifik meembahas kasus di negara tertentu.
Negara dengan populasi pengguna internet terbesar keempat di dunia ini telah meluncurkan berbagai inisiatif literasi digital yang ambisius, namun pertanyaan kritisnya adalah: Apakah Indonesia benar-benar mengadopsi MIL, atau hanya literasi digital yang berbeda secara fundamental?
Program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital” yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2021 merupakan upaya masif dengan target melatih 50 juta masyarakat hingga 2024.
Program ini menyasar empat pilar: digital ethics,digital safety,digital skill, dandigital culture. Pada 2021 saja, program ini menyelenggarakan 20.000 pelatihan yang menjangkau lebih dari 12,4 juta peserta di 514 kabupaten/kota. Entah apakah masih dilanjutkan setelah 2024.
Dalam pendidikan formal, Kurikulum Merdeka memasukkan Informatika sebagai mata pelajaran wajib di SMP dan SMA. Melalui kerja sama dengan organisasi seperti Mafindo, Kemendikbud mengembangkan Toolkit MIL untuk guru dan siswa kelas 7-12 melalui Social Media 4 Peace Phase II UNESCO.
Toolkit ini untuk memudahkan integrasi MIL dalam berbagai mata pelajaran, dan literasi digital kini diajarkan di lebih dari 60.000 sekolah. Namun, MIL masih terpinggirkan. Naskah Akademik Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) terbitan Kemendikdasmen (Februari 2025) mengungkapkan kebingungan konseptual yang serius.
Dokumen ini mengutip definisi UNESCO tentang literasi digital (2018) dan kemudian menyebutkan “literasi media dan informasi” dalam konteks yang sama, seolah-olah keduanya identik. Kutipan dari dokumen tersebut menyatakan:
“UNESCO (2018) mengusulkan definisi literasi digital sebagai kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan aman dan sesuai melalui teknologi digital… Kemampuan di bidang literasi digital ini mencakup kompetensi yang sering disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media.”
Masalahnya: UNESCO tidak pernah mendefinisikan MIL sebagai bagian dari literasi digital. Justru sebaliknya. Literasi digital atau melek digital adalah framework terpisah dan berbeda dari MIL yang sudah UNESCO kembangkan sejak jauh sebelumnya.
Pada 2018, UNESCO membuat “A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2” yang fokus pada keterampilan digital untuk pekerjaan dan kewirausahaan dalam konteks SDG 4.4.2.
Adapun MIL adalah konsep yang jauh lebih luas dan mendalam. MIL mencakup kemampuan berpikir kritis tentang media, evaluasi kredibilitas dan bias sumber informasi, pemahaman sistem dan kepemilikan media, etika informasi, serta kemampuan berpartisipasi secara demokratis di ruang informasi.
Dalam materi Koding dan KA, hanya satu dari enam elemen yaitu Literasi dan dan Etika KA yang mengarah ke soft skills. Sementara literasi digital lebih fokus pada kemampuan teknis menggunakan teknologi digital. Pencampuradukan konsep ini bisa mengundang konsekuensi serius.
Ketika Indonesia mengklaim telah mengintegrasikan “literasi media dan informasi” melalui program literasi digital dan mata pelajaran Informatika, yang sebenarnya terjadi adalah implementasi literasi digital dengan elemen MIL yang terfragmentasi—bukan MIL komprehensif versi UNESCO.
Berdasarkan pola regional yang terungkap dalam laporan UNESCO, Indonesia kemungkinan besar masuk dalam kategori 22 negara di Asia-Pasifik yang mengintegrasikan konten terkait MIL namun dengan penekanan berlebihan pada literasi digital.
Ini sejalan dengan temuan bahwa hampir setengah negara di kawasan menunjukkan pendekatan terbatas yang memprioritaskan keterampilan teknis di atas dimensi berpikir kritis. Lebih aneh lagi, di Indonesia “Koding dan KA” jadi mata pelajaran opsional karena jebakan nomenklaturnya.
Indonesia berisiko menghasilkan generasi yang mahir menggunakan teknologi tetapi tidak memiliki kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi, mengenali manipulasi media, atau berpartisipasi secara bermakna dalam demokrasi digital.
Inisiatif seperti Toolkit MIL yang dikembangkan dengan UNESCO dan Mafindo menunjukkan arah yang benar. Namun selama kebijakan nasional masih mencampur-adukkan konsep literasi digital dengan MIL, implementasi akan tetap parsial dan tidak sistematis.
Indonesia perlu melakukan klarifikasi konseptual yang jelas, mengembangkan kebijakan MIL mandiri yang komprehensif, dan memastikan bahwa guru memahami perbedaan fundamental antara mengajarkan keterampilan digital dan mengembangkan literasi kritis tentang media dan informasi.
Tantangan Indonesia mencerminkan dilema yang lebih luas: dalam kegilaan untuk “digitalisasi pendidikan,” banyak negara melupakan bahwa teknologi tanpa pemikiran kritis hanyalah alat tanpa kompas. Dan di era disinformasi yang diperkuat AI, kompas itulah yang paling kita butuhkan.
Ketika Keterampilan Digital Bukan Segalanya
Selama lebih dari tiga dekade, UNESCO telah memposisikan MIL sebagai elemen esensial kompetensi abad ke-21—fondasi bagi perkembangan demokrasi, kebebasan, dan perdamaian.
MIL bukan hanya tentang mengoperasikan teknologi atau mencari informasi di internet. Ia merupakan kemampuan komprehensif untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara kritis dan etis.
Namun penelitian yang memetakan kondisi MIL di 194 negara anggota antara Februari dan Juni 2025 menemukan realitas yang jauh dari ideal. Hanya 84 negara—atau 43 persen—yang telah mengintegrasikan elemen MIL ke dalam kurikulum pendidikan formal mereka.
Lebih mengkhawatirkan lagi, 56 negara lainnya (29 persen) memang memasukkan elemen MIL, tetapi membatasinya hanya pada keterampilan teknis digital. Ini termasuk dalam kasus Indonesia.
Ini bukan sekadar masalah semantik. Negara-negara yang membatasi MIL pada keterampilan digital, mengabaikan dimensi paling krusial: kemampuan berpikir kritis untuk menilai kredibilitas informasi, memahami bias algoritmik, dan mengenali manipulasi media.
Siswa mungkin belajar cara menggunakan teknologi, tetapi tidak memahami implikasinya terhadap sistem media, etika informasi, atau bagaimana AI memengaruhi keputusan mereka.
Di era AI generatif dapat menciptakan deepfake yang meyakinkan dalam hitungan detik, pendekatan yang hanya fokus pada keterampilan teknis ini ibarat memberikan seseorang kunci mobil tanpa mengajarkan aturan lalu lintas.
Dilema Pendekatan Lintas Kurikulum
Dari 84 negara yang telah memasukkan aspek MIL ke dalam kurikulum sekolah, mayoritas (56 negara) mewajibkannya sebagai komponen pendidikan. Ini adalah kabar baik. Tapi hanya 8 negara yang merancang kursus MIL sebagai mata pelajaran terpisah.
Namun yang menarik—dan sekaligus problematis—adalah konsensus luas tentang pendekatan lintas kurikulum: 75 negara merancang MIL untuk diajarkan melalui berbagai mata pelajaran, bukan sebagai mata pelajaran tersendiri.
Pendekatan ini memiliki logikanya. Mengintegrasikan MIL ke dalam pendidikan kewarganegaraan, bahasa dan sastra, serta ilmu sosial dapat membantu peserta didik menghargai aplikasinya dalam berbagai aspek kehidupan sosial.
Namun ia juga membawa risiko: MIL bisa hilang dan terpinggirkan di antara prioritas mata pelajaran lain. Tanpa mata pelajaran khusus, sulit untuk memantau, mengukur, dan mempertahankan dampak MIL dalam jangka panjang.
Rekomendasi UNESCO adalah pendekatan campuran—kombinasi antara mata pelajaran mandiri dan integrasi multi-subjek—sebagai strategi paling efektif untuk memastikan MIL tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar tertanam dalam pengalaman belajar siswa.
Minimnya kehadiran MIL di universitas mengungkap kesenjangan besar yang melemahkan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan kapasitas MIL tingkat lanjut yang spesifik untuk disiplin ilmu tertentu.
Ekosistem Multi-Pemangku Kepentingan
Penelitian juga memetakan siapa saja yang terlibat dalam upaya integrasi MIL di tingkat nasional. Hasilnya menunjukkan ekosistem multi-aktor yang beragam, meski tidak merata.
Lembaga pemerintah terlibat di hampir setiap negara (188 dari 194), yang merupakan perkembangan positif mengingat peran krusial negara dalam desain kurikulum dan kerangka regulasi.
Organisasi internasional adalah kontributor paling menonjol berikutnya, aktif di 168 negara, mencerminkan sifat global advokasi MIL dan peran institusi multilateral seperti UNESCO.
Aktor masyarakat sipil terlibat di 121 negara, menunjukkan peran besar dari aktor non-negara. Namun keterlibatan institusi pendidikan hanya tercatat di 61 negara—cukup mengejutkan mengingat mereka adalah institusi yang paling tepat untuk mengimplementasikan MIL di ruang kelas.
Ini bisa mencerminkan kurangnya koordinasi atau mandat terbatas bagi institusi pendidikan dalam pengembangan MIL tingkat nasional.
Keterlibatan sektor swasta muncul di 43 negara, menunjukkan tingkat kemitraan tertentu namun masih relatif terbatas. Sementara itu, keterlibatan media (22 negara), LSM (19 negara), perwakilan diplomatik asing (8 negara), dan pusat penelitian (5 negara) jauh lebih terbatas lagi.
Menuju Masa Depan yang Lebih “Melek Media”
Tantangan lingkungan digital, plus AI generatif dan perkembangannya, membentuk ulang cara orang mengakses, menafsirkan, dan berbagi informasi. MIL lebih penting dari sebelumnya, namun integrasinya dalam pendidikan tetap tidak merata dan terpinggirkan oleh keterampilan teknis semata.
Kesenjangan ini mencerminkan masalah struktural dan kebijakan yang lebih dalam. Negara-negara dengan kebijakan MIL khusus atau hibrid menunjukkan integrasi yang lebih kuat di sekolah, tapi ada negara yang hanya membatasi MIL pada kompetensi teknis.
Disparitas regional dan perbedaan kapasitas institusional menunjukkan bahwa pengakuan terhadap pentingnya MIL saja tidak cukup—menerjemahkan kebijakan menjadi aplikasi praktis di kelas tetap menjadi tantangan signifikan.
UNESCO merekomendasikan beberapa langkah kunci: mengembangkan kebijakan MIL mandiri yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional; menerapkan pendekatan campuran antara mata pelajaran khusus dan integrasi lintas kurikulum.
Selain itu, perlu memperkuat kehadiran MIL di pendidikan dasar, menengah, dan terutama tinggi; serta membangun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, sekolah, masyarakat sipil, dan mitra internasional.
Yang paling krusial: negara-negara harus memahami dengan jelas apa itu MIL dan bagaimana ia berbeda dari literasi digital. Kebingungan konseptual bukan hanya masalah akademik—ia menentukan generasi mendatang akan menjadi konsumen pasif teknologi atau warga yang kritis.
Bagaimana sistem pendidikan merespons sekarang akan menentukan apakah generasi muda mampu menavigasi informasi secara kritis, mengevaluasi kredibilitas, dan terlibat secara efektif dalam lingkungan digital yang terus berkembang pesat.
Di tengah tsunami disinformasi dan revolusi AI, kemampuan untuk berpikir kritis tentang informasi bukan lagi kemewahan—ia adalah garis pertahanan pertama untuk demokrasi, kesejahteraan sosial, dan perdamaian global.
*Photo by ThisisEngineering via Unsplash