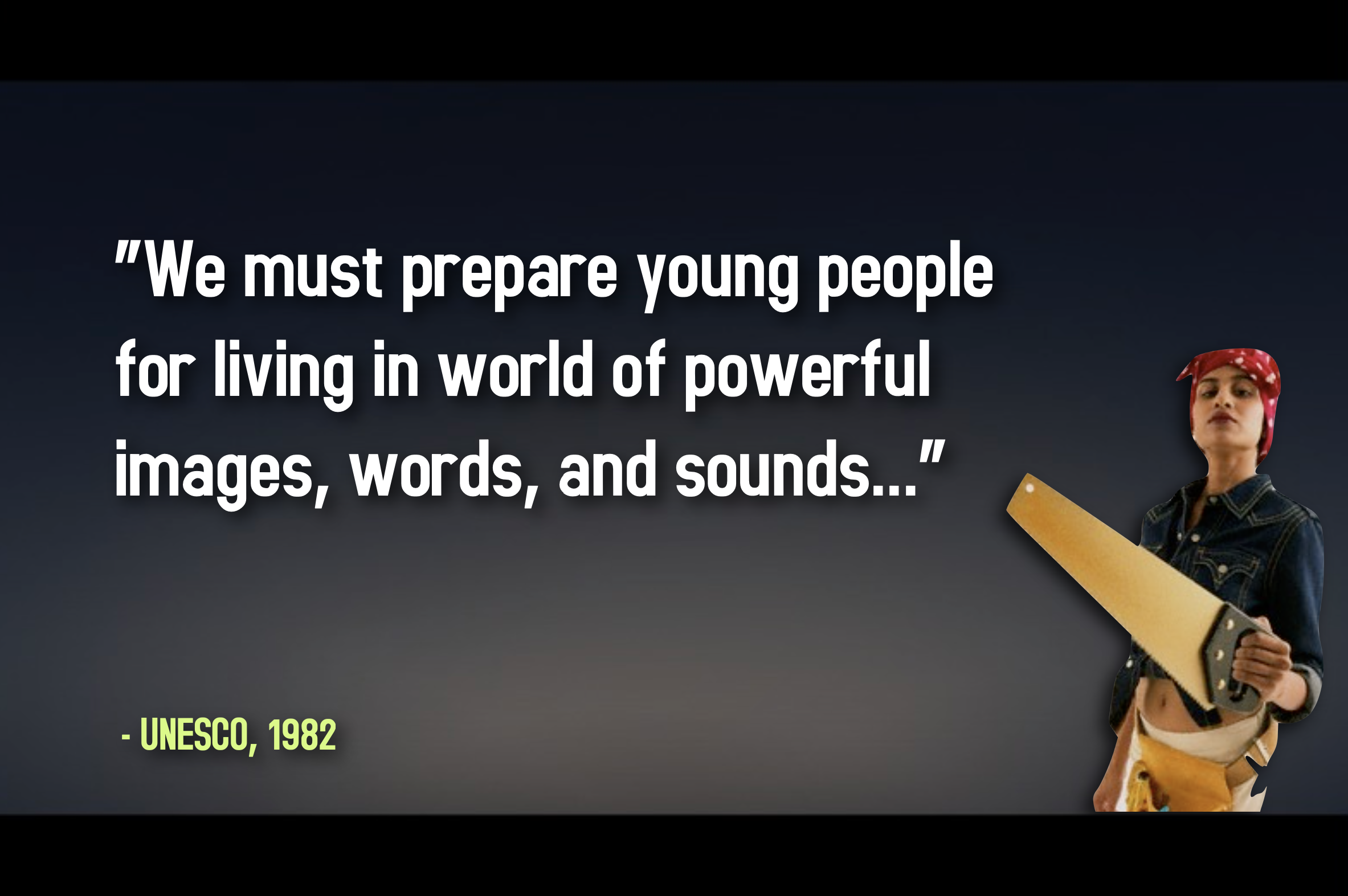Membaca, ternyata bukan aktivitas yang mudah. Menangkap apa yang dikemukakan, persis seperti apa yang dimaksudkan “penulisnya”, butuh keahlian. Terutama dalam artikel ini, kita ingin “membaca” Borobudur.
Borobudur, sudah menjadi obyek penelitian sejak dulu, baik oleh para arkeolog maupun para ahli seni rupa. Selain karena Candi Borobudur digadang sebagai salah satu candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur juga menyimpan banyak misteri lain.
Adalah Prof. Dr. Primadi Tabrani (1935-2019), Guru Besar Fakultas Seni Rupa ITB, Bandung, yang berupaya selama bertahun-tahun menemukan “cara baca” bahasa rupa yang ada di sekeliling kita.
Mulai dari cara anak-anak menggambar, kaitannya dengan bahasa rupa di jaman pra-sejarah, bahasa rupa yang digunakan dalam wayang beber Jaka Kembang Kuning, hingga kemudian cara membaca relief Borobudur.
Penelitian ini berujung dalam disertasi doktoral-nya setebal 1651 halaman.
Candi Borobudur dibangun berdasarkan kitab tertulis yang dimanifestasikan dalam bentuk rupa, relief dan patung batu atau arca (di dalam stupa).
Dengan mempelajari dinding-dinding Borobudur, hingga arca-arca di akhir perjalanan mengitari Borobudur, seorang calon pendeta Buddha bisa “belajar”. Borobudur, tak ubahnya sebuah sekolah.
Tetapi bagi generasi modern, tidak mudah menafsirkan bahasa rupa pada relief Borobudur. Selain karena tidak mungkin lagi bertanya kepada “penulisnya”, tampilan bahasa rupa dalam relief candi tidak serupa dengan bahasa rupa yang kita kenal sekarang.
Membaca tanpa memahami bahasa
Foto yang terbaik yang bisa didapat di internet, dari web https://www.photodharma.net. Dibuat oleh seseorang yang mengaku bernama Anandajoti Bhikkhu. Kalau beliau ini membuat fotonya, berati ia sudah pernah berkunjung ke Borobudur.
Sebagai contoh saja, dari Panil No. 46-49 seri Lalitavistara. Dari penelitian dari borobudur.tv berikut ini:
The Bodhisattva participates in the competitions. When the Bodhisattva attempted to demonstrate his skill as an archer, every bow that he drew broke asunder in his hands. “Is there any bow to be found here in the city that is suited to my reach and power of body?” asked Gautam.
“Your grandfather’s bow is preserved in a temple nearby, where it is honored with perfumes and garlands,” replied Gopa’s father. “but never has another man been able to bend it to his will.”
“Let the bow be brought, my lord,” answered Gautama, “so that I might make a trial of it.”
When the bow arrived, the Bodhisattva grasped it with his left hand and without rising from his seat or uncrossing his legs, he drew it back with a single finger. He then stood up and unleashed an arrow that pierced seven iron drums, a row of seven trees and an iron boar before it finally entered the ground and vanished.
Kalau kita cermati gambar reliefnya, mungkin cukup masuk akal. Dengan pemahaman terbatas mengenai apa dan bagaimana relief itu dibuat, banyak penelitian lain “bingung” dengan bahasa rupa dalam relief tersebut.
Menggunakan grammar yang dianggap biasa dipakai, begitulah kesimpulan dari cerita pada panel tersebut. Pertanyaannya, apakah benar begitu ceritanya?
Benarkah Bodhisattva mengambil anak panah dengan tangan kirinya tanpa mengubah posisi duduknya? Benarkah dia yang duduk di atas singgasana itu?
Cara unik membaca Borobudur
Jadi, bagaimana cara membaca panel Borobudur itu? Nah, kira-kira begini penjelasannya:
Teks yang dirupakan pada panil bercerita tentang sayembara memanah, tersebar di 3 halaman dan mencakup 4 paragraf cerita. Secara naluriah, kita memandang relief ini seperti gambar diam (still picture), layaknya hasil jepretan kamera.
Padahal tidak begitu. Relief ini menggunakan lapisan (layer), yang menunjukkan dimensi waktu, dan pergeseran posisi tokoh sebagai penanda sekuen.
Lapis terdalam, menunjukkan peristiwa yang terjadi lebih dulu. Arah pergeseran, dari kanan ke kiri menunjukkan urutan waktu. Dalam panel ini sebenarnya terdapat 2 lapisan utama.
Lapis pertama, tampak di “latar belakang”: Sederetan peserta memanah yang sudah selesai memanah. Anggap saja latar muka yang ada tokoh sedang memanah itu belum ada.
Sekarang coba lihat gambar di bawah ini, gambar relief yang telah disederhanakan. Kini latar belakangnya yang dihapus, untuk memperjelas cerita di latar depan.
Lapis kedua ini, agar tidak membingungkan, dipilah lagi menjadi beberapa gambar sesuai urutan kejadian. Ini seperti sedang menonton negatif film layar lebar.
Pada Gambar Lapis Kedua Adegan Pertama (gambar di atas), di sebelah kanan ada tokoh berpayung dan duduk di atas “singgasana”. Ia adalah si tuan rumah sayembara.
Tampaknya ia bangsawan (atau raja), karena bermahkota, dan duduk di tempat yang “ditinggikan”. Pesannya, si bangsawan atau raja ini sedang menonton sayembara.
Di sebelah kirinya ada seorang peserta dengan atribut yang mirip bangsawan pula, tapi berdiri di atas batu. Ciri ini penting, karena inilah yang mencirikan Bodhisatwa. Ia digambarkan tidak pernah menjejak tanah.
Anak panah dan busur di tangan Bodhisatwa tampak diperbesar, dan sedang “mejeng” di tangannya (mirip iklan yang suka memamerkan produk ke kamera lengkap dengan tampilan brand-nya).
Anak panah dan busur yang “diperbesar”, menandakan kedua benda itu penting (dalam teks aslinya, anak panah dan busur itu memang bukan sembarangan).
Pesannya kira-kira, Bodhisatwa menunggu giliran. Dia memang mendapat giliran terakhir.
Pada gambar Lapis Kedua Adegan Kedua, Bodhisatwa tampak berada di tengah gelanggang dan memegang anak panah, bersiap memanah.
Kemudian, gambar Lapis Kedua Adegan Ketiga, Bodhisatwa memanah ke arah 7 pohon lontar. Terlihat dalam panil, posisi Bodhisatwa sedang menarik busurnya, dan anak panah yang menancap di bagian pohon.
Cerita berakhir pada gambar Lapis Kedua Adegan Keempat dengan anak panah yang menembus 7 pohon lontar. Panah yang menembus pohon digambarkan dengan garis di tengah ketujuh pohon tersebut.
Jadi, Bodhisatwa (Buddha) tidak memanah dari atas singgasana. Tokoh di atas singgasana itu bahkan belum tentu gambaran Bodhisatwa. Ia tetap memanah sambil berdiri, dan cirinya bisa dikenali dari batu di atas kakinya.
Panil ini sebenarnya mirip komik tetapi digambarkan dalam satu panil dengan satu bingkai (frame). Bedanya, komik zaman sekarang dalam satu panil terdiri dari beberapa bingkai. Antar-bingkai dipisahkan oleh ruang kecil yang disebut closure.
Sementara, dalam panil Lalitavistara ini closure tersebut “digambarkan” dengan lapisan (layer). Pergeseran letak tokoh pun ditampilkan tanpa bingkai.
Bodhisatwa tampil tiga kali pada “latar depan”, karena menunjukkan pembabakan waktu, atau sekuen. Jadi tidak berarti ada 3 Bodhisatwa kembar, melainkan satu tokoh sedang melakukan satu aktivitas pada waktu berbeda.
Satu panel, multi layer, multi adegan, multi dimensi waktu. Inilah cara membaca Borobudur yang sebenarnya. Dan ini, hanya salah satu dari beberapa metode visualisasi yang ditemukan dari seluruh panel di Borobudur.
Metode ini, sesuai penelitian Pak Primadi, dapat ditemukan dalam gambar anak-anak. Anak seringkali menggambar dengan tokoh atau objek yang diulang, dan itu maksudnya adalah sekuen adegan tanpa bingkai.
Demikian pula, salah satu ciri khas gambar anak adalah menonjolkan objek yang dianggapnya penting. Biasanya, yang dianggap penting digambar lebih menonjol (besar atau tebal).
Bahasa rupa Timur vs Barat
Berdasarkan penelitian Pak Primadi pula, diketahui bahwa bahasa rupa yang digunakan dalam panil di Borobudur, merupakan bahasa yang unik, dan tidak ditemukan di tempat lain. Dengan kata lain, bahasa rupa khas Indonesia.
Bahasa rupa yang digunakan itu disebut sebagai Ruang Waktu Datar (RWD), yang sangat berbeda dengan cara Naturalis-Perspektif-Momen Opname (NPM) dari Barat yang selama ini kita kenal.
Secara umum, RWD lebih mementingkan gesture, sehingga tokoh digambarkan secara lengkap (kepala-kaki), sedangkan NPM sangat peduli dengan mimik wajah. Seperti close-up dalam komik (atau film).
Selama ini NPM telanjur menjadi pakem (menghegemoni), sehingga dunia pendidikan “memaksakan” bahasa NPM kepada anak. Ingat gambar dua gunung dengan jalan di tengahnya? Itu manifestasi hegemoni perspektif.
Padahal, secara alamiah anak-anak lebih mengenal RWD. Barulah pada usia tertentu mereka bisa memahami NPM.
Bahasa rupa lawas ini tidak lagi dipelajari, sehingga manusia modern kesulitan membacanya. Penelitian ini mengingatkan bahwa bahasa selalu berkembang, dan membaca relief Borobudur tidak bisa menggunakan cara-cara yang berbeda pada saat dibuat.
Bukan hanya bahasa lisan yang punya banyak varian, bahasa rupa pun demikian. Contoh dalam artikel inipun hanya salah satu varian yang ditemukan di Borobudur. Masih ada varian lain yang bisa ditemukan di panil lainnya.
*Photo by Sebastian Staines on Unsplash | Materi disarikan dari hasil diskusi dan perkuliahan Prof. Dr. Primadi Tabrani, yang bisa Anda dapat juga dari hasil penelitian doktoralnya, berjudul “Meninjau Bahasa Rupa Wayang beber Jaka Kembang Kuning, dari telaah Cara WImba dan Tata Ungkapan Bahasa Rupa Media Ruparungu Dwimatra Statis Modern, dalam hubungannya dengan Gambar prasejarah, Primitif, Anak, dan Relief cerita Lalitavistara Borobudur”. 1991. + “Bahasa Rupa”, Primadi Tabrani.