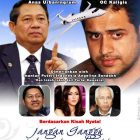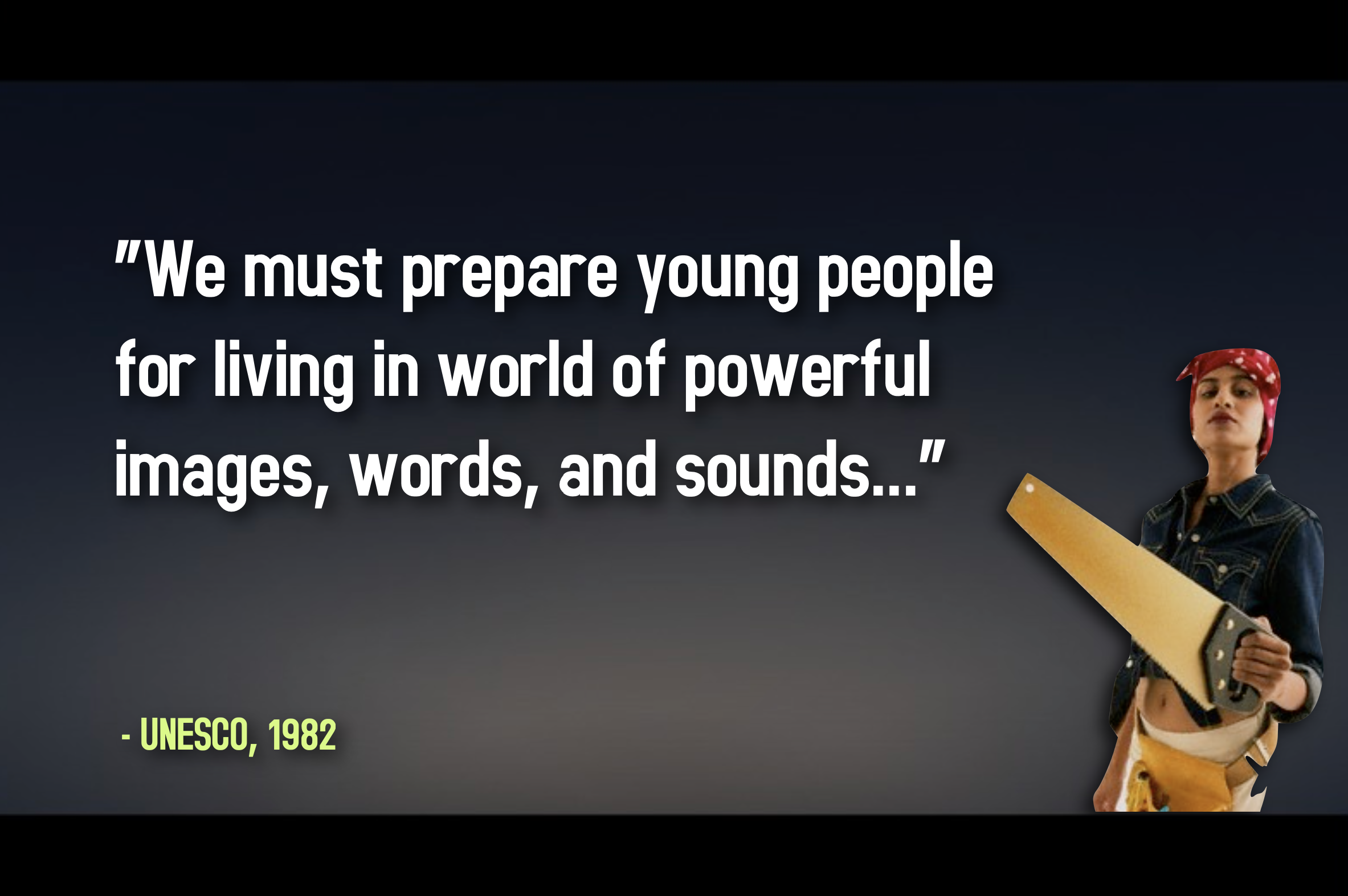Selamat datang di Surabaya, kota mikrofon yang enggak di-mute tapi lebih jujur daripada jutaan caption manis di Instagram. Lantaran admin media sosial yang lidahnya kepleset—atau mungkin memang kelepasan karena sudah terlalu lelah berpura-pura—saat jeda live Wali Kota.
Sebuah candaan viral, menguap ke udara digital: “epok-epok keliling” atau “pura-pura berkeliling”. Boom! Seketika, dinding teater megah bernama Social Media Governance runtuh, menampilkan backstage yang lusuh. Tiba-tiba, kita semua tahu bahwa di balik take sempurna Bapak Wali Kota yang gagah berani nyipratin diri di genangan air, ada skenario yang rapi.
Sang Wali Kota, dengan jurus damage control yang elegan sekaligus defensif, bilang: “Media sosial itu bukan untuk popularitas, dan bukan juga untuk menampilkan apa yang sudah dikerjakan,” katanya, seraya menyajikan data penurunan stunting (menjadi 1,6%) dan kemiskinan (turun 3,9%) sebagai bukti otentik.
Sebuah tangkisan yang lumayan cerdas, tapi ngos-ngosan. Ia harus repot memperjuangkan klaim kerja nyata itu di platform yang katanya “bukan untuk popularitas”. Politik ini benar-benar drama, plot twist yang enggak lucu!
Tragedi “epok-epok” ini bukan sekadar insiden teledor anak muda yang lupa menekan tombol mute. Ini adalah gejala krisis legitimasi di era politik panggung atau Performance Politics. Kita semua adalah audiens, tapi politisi adalah Superstar yang harus selalu tampil prima.
Dalam performance studies, ada pakar yang sangat asyik dan relevan, namanya Richard Schechner. Seorang pionir yang mengatakan bahwa kinerja (performance) bukan hanya terjadi di atas panggung teater, tapi juga merasuk ke dalam ritual, kehidupan sehari-hari, dan, tentu saja, politik.
Schechner, dalam bukunya Performance Theory (2003), membedakan antara efficacy (keefektifan, tujuan ritual yang nyata) dan entertainment (hiburan, tujuan hiburan). Masalahnya, di panggung politik digital 2025, kedua hal ini telah terjalin dalam braid yang rumit, seperti tali kepang yang tak terpisahkan—sulit untuk diurai tanpa merusak seluruh anyaman.
Pusat teori Schechner yang paling nyentil adalah konsep perilaku yang dipulihkan (Restored Behavior). Ia menjelaskan bahwa:
“Perilaku yang dipulihkan adalah tindakan fisik atau verbal yang tersusun—sepotong, bukan keseluruhan—yang dipindahkan dari konteks saat ia ‘diciptakan’ dan dipentaskan di tempat dan waktu yang berbeda. Perilaku tersebut adalah seperti rekaman kaset atau gulungan film, yang dapat ‘diedit’, ‘diatur’, dan ‘dieksekusi’ lagi dan lagi.” (Schechner).
Mari kita bedah kalimat admin yang bocor: “Kalau seperti ini, Mat, videonya kan bagus. Kita simpan saja dulu kalau nanti hujan bisa dipakai, seolah-olah bapak turun… epok-epok keliling.” (Barometer Jatim, 31 Oktober 2025).
Kalimat ini adalah deskripsi paling jujur tentang Perilaku yang Dipulihkan dalam konteks politik.
- Tindakan yang Tersusun: Aksi blusukan atau peninjauan lapangan yang dilakukan Wali Kota adalah tindakan yang tersusun, difilmkan dari angle terbaik.
- Dipindahkan dari Konteks: Tindakan ini direkam saat cuaca mungkin cerah, tetapi dipindahkan (di-posting) ke konteks saat hujan atau banjir melanda (masa depan), seolah-olah spontan sedang terjadi.
- Dapat Dieksekusi Lagi dan Lagi: Video itu disimpan sebagai aset, sebagai stock shot dapat “digunakan kembali” (re-run), menciptakan ilusi kehadiran dan kepedulian yang abadi, tanpa sang pejabat harus basah kuyup setiap kali banjir datang.
Di sinilah letak jurang kegagalan komunikasi politik modern. Ketika seorang politisi terjebak dalam obsesi menciptakan konten yang sempurna, efficacy tereduksi menjadi entertainment. Kerja jadi konten, bukan kewajiban. Kewajiban dipentaskan seolah-olah spontan, padahal itu adalah taping berulang-ulang dari sebuah naskah “Pemimpin Merakyat Blusukan”.
Maka, wajar jika muncul sindiran sarkastik, bukan pantun, melainkan sekadar rima yang terstruktur: Kerja keras di balik layar sering luput dari layar, pencitraan semata justru membuatnya terlihat tenar dan benar. Legitimasi pun tergerus perlahan-lahan dan kian gentar oleh onar yang menyebar.
Politik hari ini telah masuk ke dalam pusaran candu like. Legitimasi politik tak lagi cukup hanya bermodal UU dan hasil pemilu; ia harus di-endorse oleh jempol digital dan retweet. Pejabat di era 2025, tak peduli ia mantan staf atau politisi kawakan, semua jadi influencer dadakan. Mereka terjebak dalam rat race yang absurd: harus bekerja, tapi yang terpenting, harus terlihat bekerja.
Jika Wali Kota benar-benar yakin bahwa media sosial bukan untuk popularitas, mengapa ia menolak pengunduran diri sang admin, dan malah membelanya sebagai anak muda yang “kreatif dan bertanggung jawab”? (RRI, 3 November 2025). Plot twist yang menarik!
Bukankah ini justru menegaskan bahwa tim pembuat konten epok-epok itu penting dan berharga bagi kelangsungan narasi politiknya? Admin tersebut adalah aktor kunci yang memastikan restored behavior sang pejabat bisa terus diproduksi, di-upload, dan diyakini oleh publik.
Inilah krisis otoritas dan legitimasi digital. Kredibilitas tidak lagi dibentuk oleh otoritas lembaga atau rekam jejak kerja bertahun-tahun, melainkan oleh viralitas dan pengulangan narasi. Ketika mic bocor, seluruh viralitas yang dibangun bisa runtuh dalam sekejap, dan yang tersisa adalah kecurigaan.
Skeptisisme publik terhadap politik kinerja ini memiliki implikasi jangka panjang. Ketika publik mulai meyakini bahwa segala upaya yang tampak di media sosial hanyalah akting atau pura-pura (epok-epok), maka hasil kerja nyata via statistik resmi pun akan disaring melalui lensa kecurigaan yang sama. Jangan-jangan data stunting ini juga cuma skenario edit?
Kecurigaan adalah virus terganas bagi demokrasi yang sehat, karena ia merusak ikatan kepercayaan antara yang memerintah dan yang diperintah.
Kita juga bisa menghubungkan “epok-epok keliling” dengan obrolan netizen soal tren Performative Male/Female. Konsep performative, yang populer di ranah gender, dibawa oleh filsuf Judith Butler. Butler, dalam Gender Trouble (1990), memandang gender bukan sebagai sesuatu yang esensial, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh tindakan.
Gender itu, katanya, adalah kata kerja (verb), bukan kata benda (noun). Kita menjadi seorang pria atau wanita melalui serangkaian tindakan yang kita ulangi dan pentaskan untuk diakui oleh masyarakat.
Nah, ketika netizen menyebut Performative Male (misalnya, pria yang pura-pura suka matcha latte, pakai tote bag Labubu, atau baca buku feminis, bukan karena keyakinan, tapi demi menarik perhatian perempuan), mereka sedang mengkritik hilangnya autentisitas. Perilaku tersebut akting yang dikonstruksi untuk mencapai validasi sosial/romantis, persis seperti yang Butler jelaskan.
Hubungannya dengan Wali Kota? Pemerintahan yang epok-epok adalah perwujudan dari Performative Leadership. Pemimpin ini tahu betul apa yang diinginkan oleh audiens Gen Z dan milenial: kerentanan emosional, kehadiran real-time, dan keberanian “turun ke bawah”. Maka, diciptakanlah persona Performative Male Leader:
Ia menampilkan aksi simbolik yang woke: Blusukan ke selokan, ngopi di warung sederhana, dan tampil basah kuyup saat banjir—ini adalah simbol-simbol yang dikonstruksi untuk menggantikan kerja struktural. Padahal, motivasi utamanya bukan efficacy (menuntaskan masalah), melainkan entertainment dan validasi (like, share, dan narasi “Pemimpin Merakyat”).
Ketika narasi politik didominasi oleh performance, maka realitas teralienasi. Kebenaran (kerja keras) jadi tidak penting; yang penting adalah representasi (citra kerja keras). Pohon jadi tak lebih penting dari bayangannya. Alhasil tercipta jurang komunikasi: pejabat sibuk mengedit video di studio, eh masalah di lapangan terus menumpuk tanpa solusi yang fundamental.
Pelajaran dari insiden mic bocor ini bukan soal siapa yang salah—meski admin yang jujur itu layak dapat standing ovation karena menjadi whistleblower tanpa disengaja. Pelajaran utamanya adalah: Media sosial telah mengubah kerja politik menjadi seni peran yang haus validasi instan.
Padahal, kita enggak butuh politisi yang hanya pandai berlagak dan bisa memainkan lakon di depan kamera. Kita butuh birokrasi yang bekerja senyap dan terukur di belakang layar, bukan sibuk mengurus angle kamera terbaik saat blusukan agar terlihat merakyat dan mendekat.
Kita perlu menuntut efficacy, bukan sekadar entertainment. Kita butuh pejabat yang melihat warga sebagai mitra dialektis, bukan sekadar audiens pasif yang harus diisi dengan konten yang bersih dan steril dari kegagalan.
Politik yang baik tidak membutuhkan take kedua. Ia hanya membutuhkan komitmen dan konsistensi dalam bekerja, tanpa drama yang memperdaya dan menghina logika publik. Kita enggak butuh aktor. Kita cuma butuh pemimpin yang tekun menjalankan tujuan. Kerja tulus tak haus like dan perhatian.
*Photo by Jan Antonin Kolar via Unsplash