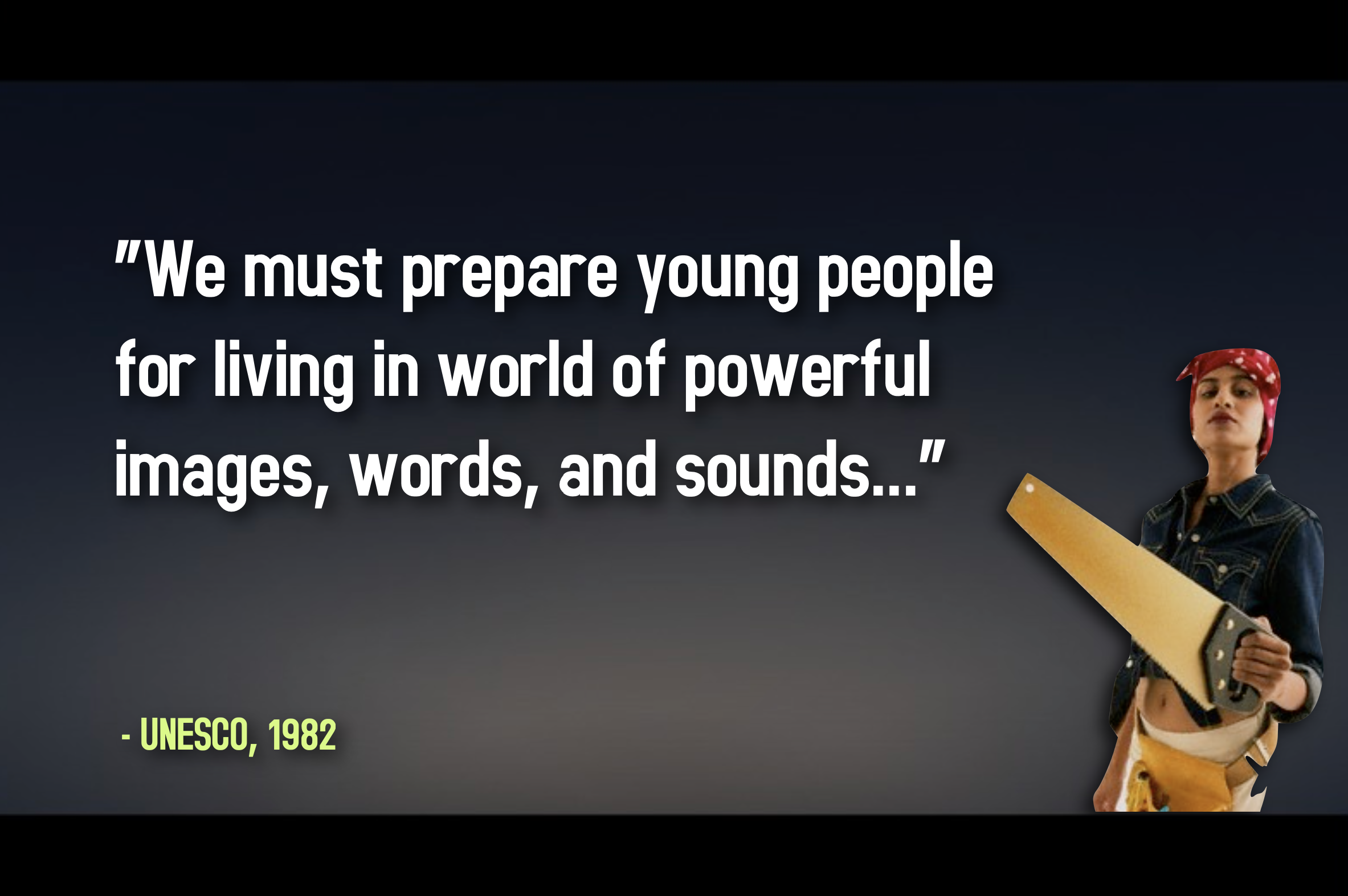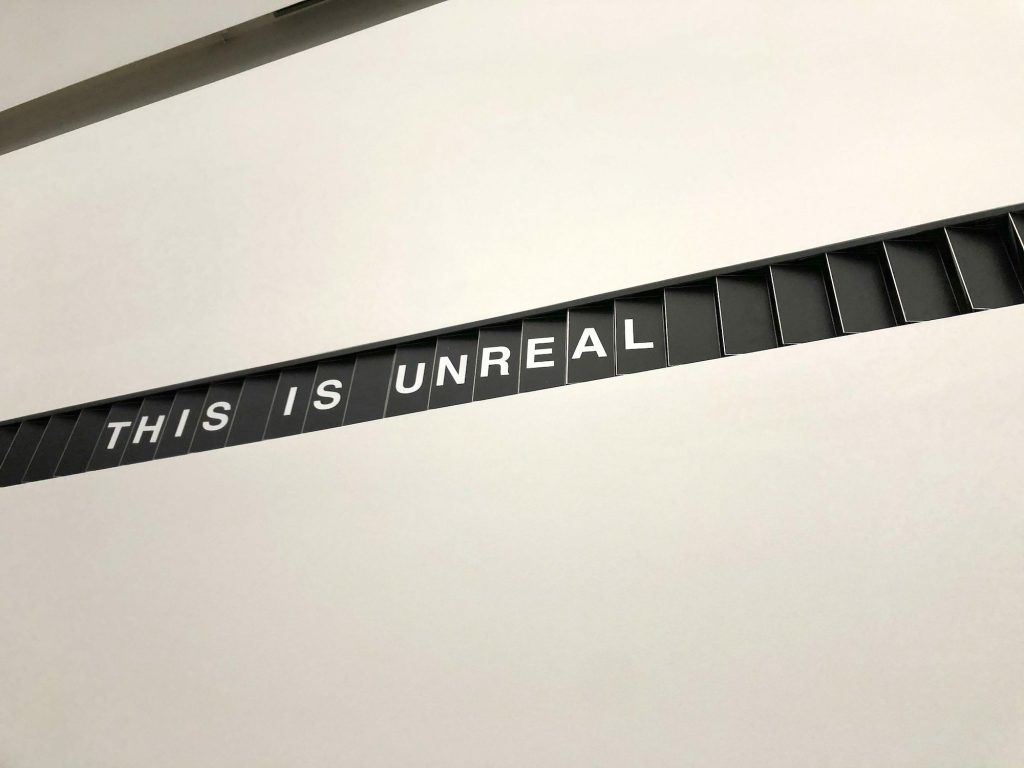
Filsuf politik Hannah Arendt pernah menyatakan tujuan dari erosi kebenaran adalah untuk mengendalikan dan memanipulasi massa; ketika tak seorangpun percaya pada apapun, orang-orang mudah dimanipulasi. Inilah yang kita lihat hari-hari belakangan ini. Disinformasi dan misinformasi semakin merajalela atas nama stabilitas.
Tulisan ini berupaya menjelaskan fenomena tersebut, sekaligus menjajaki potensi jalan keluarnya. Pembahasan disarikan dari presentasi Dr. Joe Pierre, seorang psikiater dan pakar delusi serta keyakinan palsu, yang berbicara di forum Commonwealth Club World Affairs. Ia juga penulis buku “False: How Mistrust, Disinformation, and Motivated Reasoning Make Us Believe Things That Aren’t True”.
Dr. Pierre menekankan bahwa keyakinan keliru yang dipegang teguh meskipun ada bukti yang jelas bertentangan—atau yang disebutnya “fakta alternatif”—memiliki konsekuensi yang mengkhawatirkan. Dampak utamanya adalah hilangnya kepercayaan pada institusi krusial seperti pemerintah, media, dan sains, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi secara efektif dan berkomunikasi jujur.
Erosi kepercayaan ini memperkuat tren tribalisme, saat masyarakat mengelompokkan diri berdasarkan kesamaan keyakinan, memperdalam perpecahan sosial, dan menciptakan lingkungan yang rentan terhadap munculnya pemimpin otoriter yang menolak konsensus ilmiah.
Lebih jauh, paparan informasi yang salah secara terus-menerus dapat membebani psikologi individu, menyebabkan peningkatan stres, kemarahan, dan bahkan melegitimasi kekerasan. Konsekuensi negatif ini merambah ke berbagai aspek kehidupan, dari kesehatan masyarakat—seperti penolakan vaksin atau perubahan iklim—hingga stabilitas politik dan ekonomi global.
Contoh lain yang terlihat di berbagai belahan dunia terkait keyakinan palsu dalam isu politik. Keyakinan palsu mengenai tingkat kejahatan, imigrasi, inflasi, dan keadaan ekonomi telah memengaruhi hasil pemilihan presiden di AS pada 2024. Fenomena ini berpotensi mengarah pada otoritarianisme baru, pemimpin yang terang-terangan menolak konsensus ilmiah.
Dr. Pierre menyoroti bahwa kerentanan terhadap keyakinan palsu ini tidak berarti individu mengalami delusi atau kurang cerdas, melainkan lantaran proses kognitif normal yang kita miliki. Sayangnya, secara historis, bidang psikologi dan psikiatri kurang memberi perhatian memadai mengenai sebab orang “normal” bisa berpegang teguh pada keyakinan palsu tersebut.
Memahami keyakinan palsu
Dr. Pierre pun menawarkan kerangka berpikir yang lebih sederhana dan universal untuk memahami keyakinan palsu, yang disebutnya sebagai model Tiga M: (1) Mistrust atau ketidakpercayaan; (2) Misinformation atau Misinformasi; dan (3) Motivated Reasoning atau Penalaran Bermotivasi.
Pertama, Mistrust atau ketidakpercayaan epistemik mengacu pada erosi kepercayaan terhadap informasi dan sumber-sumber arus utama, termasuk institusi otoritas dan keahlian ilmiah. Di era internet, akses informasi tanpa batas memungkinkan pendapat awam sejajar dengan narasumber kredibel, seringkali membuat influencer menggantikan ahli.
Penurunan kepercayaan publik terhadap ilmuwan, khususnya pascapandemi, menunjukkan banyak yang meyakini ada bias ilmuwan atau metode ilmiah dapat dimanipulasi, alih-alih mempertahankan skeptisisme berbasis bukti.
Kedua, Misinformation atau misinformasi, meskipun ada sejak lama, diperkuat secara signifikan oleh media baru seperti TV kabel dan internet. Platform-platform ini membuat publik kesulitan membedakan sumber yang andal dari yang tidak, memungkinkan informasi palsu bergerak lebih jauh dan lebih cepat karena sensasional dan mengundang emosi.
Fenomena illusory truth effect menunjukkan bahwa semakin sering seseorang terpapar misinformasi, semakin mudah mereka mempercayainya. Di dunia pasca-kebenaran ini, keuntungan viralitas seringkali mengalahkan pemeriksaan fakta, menciptakan realitas alternatif yang menggantikan kebenaran objektif.
Ketiga, Motivated Reasoning atau penalaran bermotivasi menjelaskan mengapa individu berpegang teguh pada keyakinan palsu. Ini seiring dengan bias konfirmasi, di mana seseorang cenderung mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada, sambil mengabaikan yang bertentangan. Penalaran bermotivasi lebih mendalam: kita menilai informasi berkualitas tinggi jika mendukung afiliasi ideologis kita, dan menolaknya sebagai “sampah berkualitas rendah” jika berlawanan.
Ini menjelaskan polarisasi pandangan terhadap sumber berita dan mengapa orang dapat memegang keyakinan kuat berdasarkan bukti yang lemah, menipu diri sendiri untuk menghindari pengakuan kesalahan. Kecenderungan ini mengarah pada pemikiran kelompok ideologis dan pengelompokan partisan yang kuat pada isu-isu krusial seperti vaksin dan perubahan iklim.
Resep untuk dunia pasca-kebenaran
Untuk melawan gelombang disinformasi yang mengancam ini, Dr. Pierre mengajukan resep di tingkat individu dan masyarakat. Di tingkat individu, ia menyarankan “Trinitas Suci Deteksi Kebenaran”:
- Kerendahan Hati Intelektual (Intellectual Humility): Kesediaan untuk mengakui bahwa pengetahuan dan keyakinan kita tidak sempurna dan mungkin salah. Sikap ini mendorong evaluasi ulang informasi dan penerimaan koreksi berbasis bukti.
- Fleksibilitas Kognitif (Cognitive Flexibility): Kemampuan untuk mendengarkan dan memahami perspektif lain, serta bersedia mengubah pikiran jika bukti mendukungnya. Ini krusial untuk dialog lintas perbedaan dan menghindari “gelembung filter.”
- Pemikiran Analitis (Analytical Thinking): Pendekatan hati-hati dan metodis dalam mengevaluasi informasi, mempertanyakan sumber, mencari bukti, dan mempertimbangkan bias. Ini adalah penangkal langsung terhadap berita palsu, terutama ketika dihadapkan pada informasi yang terlalu sesuai dengan keinginan.
Di tingkat masyarakat, solusi jangka panjang melibatkan pemulihan dan penguatan kepercayaan pada institusi otoritas. Pemerintah, lembaga ilmiah, dan media kredibel harus berkomitmen pada transparansi yang lebih besar, mengakui kesalahan, dan melibatkan publik secara aktif.
Selain itu, reformasi sistem pendidikan di seluruh jenjang usia sangat penting. Kurikulum harus mencakup pengajaran filosofi sains, pemikiran analitis, dan literasi media atau melek media—membekali siswa untuk mengenali sumber kredibel dan taktik disinformasi.
Langkah konkret lain untuk mengurangi penyebaran misinformasi meliputi teknik inokulasi seperti pre-bunking, yang memaparkan individu pada versi misinformasi yang dilemahkan atau penjelasan taktik disinformasi untuk membangun kekebalan kognitif.
Kemudian, perlu upaya mengurangi misinformasi yang sudah beredar melalui moderasi konten yang efektif oleh platform daring, pemasaran kebenaran yang lebih baik oleh pihak otoritatif, dan meminta pertanggungjawaban penyebar disinformasi melalui langkah hukum atau sanksi sosial.
Dr. Pierre menyimpulkan bahwa aktivisme diperlukan untuk menjaga kewarasan dan melawan keyakinan palsu yang berbahaya. Ini berarti membela sains, kebenaran, hak-hak sipil, perawatan medis berbasis bukti, atau kebijakan iklim yang sehat. Membangun koalisi, berinteraksi dengan lawan ideologis, dan fokus pada sumber disinformasi adalah kunci.
Sebagaimana sejarah demokrasi lain yang beralih ke otokrasi menunjukkan, tindakan harus diambil sekarang, karena ketidakaktifan akan menjamin akhir demokrasi. Melawan keyakinan palsu di dunia pasca-kebenaran bukan hanya perjuangan untuk integritas informasi, tetapi juga untuk masa depan demokrasi dan kohesi sosial kita.
Tonton video selengkapnya di sini:
Photo by Andryck Lopez on Unsplash