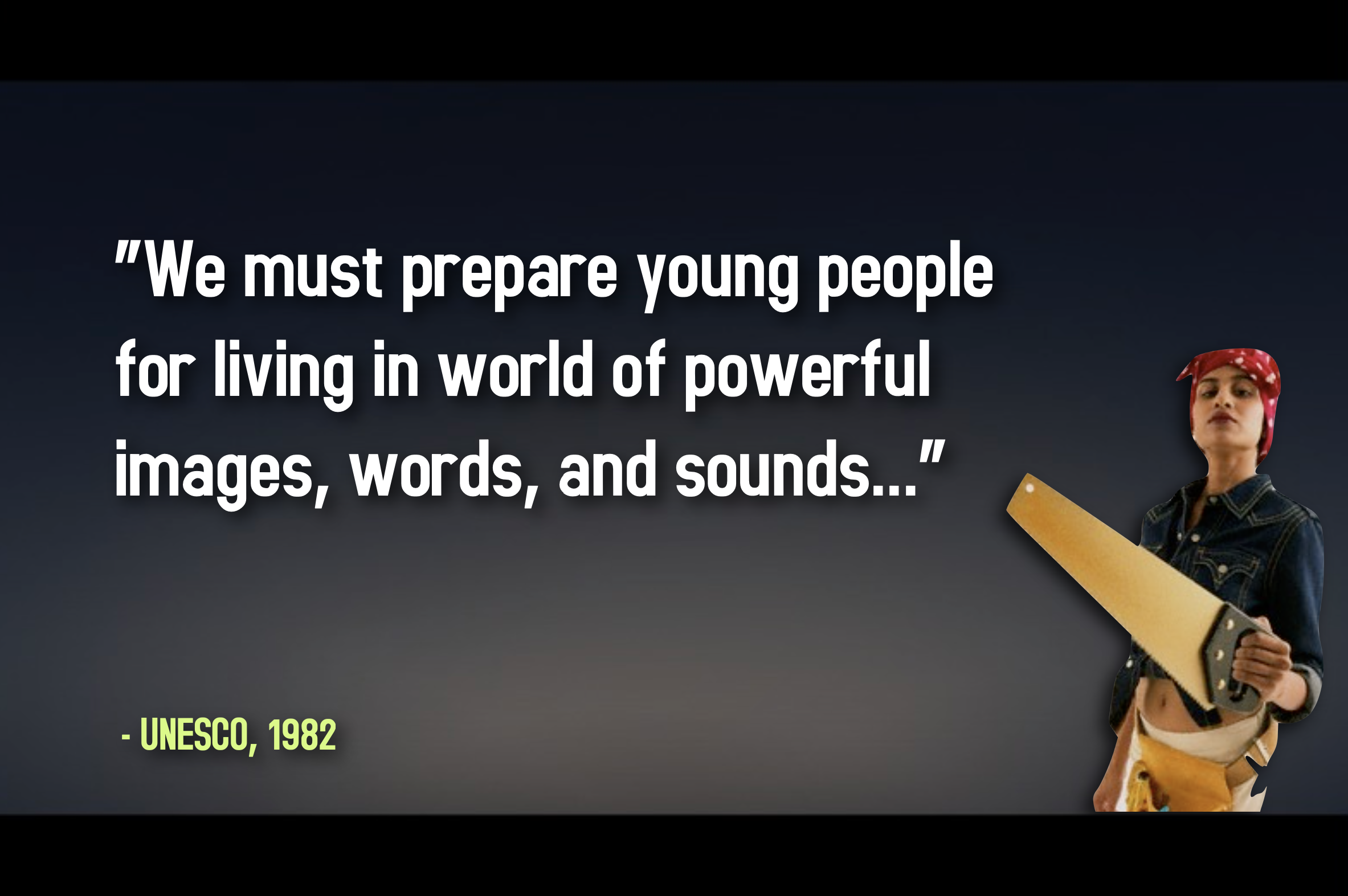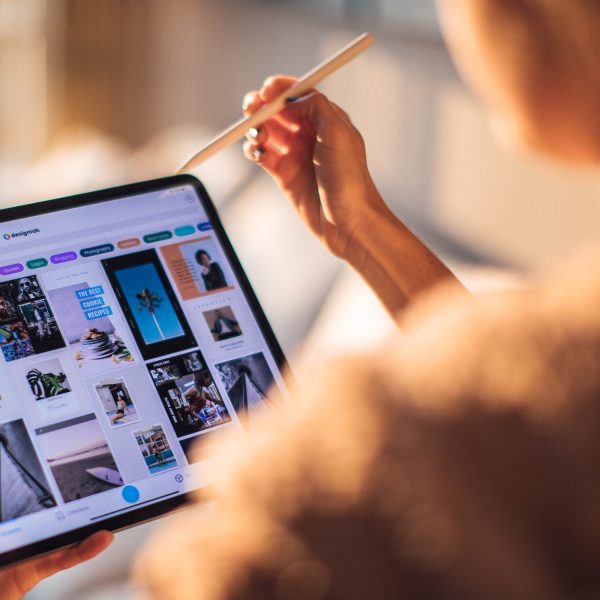
Pedoman Tata Kelola Platform Digital yang digagas UNESCO menyajikan kerangka ideal untuk menavigasi kompleksitas ruang digital. Banyak yang harus dikelola, meliputi ekosistem digital yang luas.
Tata kelola ini menjamin bagaimana ruang digital senantiasa menjadi tempat yang aman, terbuka, dan mendukung kebebasan berekspresi bagi semua, tanpa mengorbankan hak asasi manusia lainnya.
Adapun yang dimaksud platform, adalah perusahaan atau layanan digital yang menyediakan ruang bagi pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi, menyebarkan, dan mengonsumsi konten.
Ada lima prinsip sebagai acuan pengembangan tata kelola platform digital yang inklusif, yaitu (1) uji tuntas hak asasi manusia, (2) standar hak asasi manusia internasional, (3) transparansi, (4) aksesibilitas informasi, dan (5) tanggung jawab.
Pengelolaan ini tidak sekadar memoderasi atau menghapus konten ilegal/berbahaya seperti disinformasi, ujaran kebencian, atau hasutan kekerasan, tetapi memastikan keberagaman ekspresi budaya tetap terjaga dan tidak terpinggirkan oleh algoritma.
Operasi internal platform juga menjadi aspek yang diatur. Ini termasuk bagaimana desain platform memengaruhi perilaku pengguna, bagaimana algoritma bekerja dalam mengkurasi dan merekomendasikan konten, serta pengelolaan data pengguna.
Pengelolaan juga harus mencakup interaksi pengguna dengan platform. Harus ada mekanisme pelaporan yang efektif dan mudah diakses, jalur banding yang adil bagi pengguna, serta layanan platform yang dapat diakses oleh semua secara inklusif.
Terakhir, akuntabilitas dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam tata kelola digital. Ada negara yang menciptakan kerangka regulasi berlandaskan HAM, platform yang mematuhi standar, serta masyarakat sipil dan akademisi dalam mengawasi dan memberi masukan.
Sejauh ini Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, telah menyatakan dukungan terhadap Pedoman Tata Kelola Platform Digital UNESCO yang dirilis pada 2024 tersebut.
“Kita perlu memperkuat ekosistem digital dengan program-program konkret yang mendorong pemberdayaan internet secara positif, produktif, dan inklusif,” ungkapnya saat itu.
Indonesia memiliki regulasi platform digital melalui UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pelindungan Data Pribadi, serta Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, yang mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik privat.
Pemerintah Indonesia juga mengadopsi DMA dan DSA dari Uni Eropa sebagai acuan dalam mengembangkan tata kelola platform digital. DMA bertujuan menjaga persaingan pasar yang sehat dengan mengatur perilaku platform digital besar sebagai gatekeepers.
Sementara, DSA berfokus pada keamanan konten dan tanggung jawab platform, terutama yang berskala sangat besar (Very Large Online Platforms/VLOPS) dan mesin pencari (Very Large Online Search Engines/VLOSES).
Pertanyaan yang masih muncul: Seberapa jauh relevansi dan implementasi pedoman luhur UNESCO ini dapat berakar kuat di Indonesia, sebuah negara dengan lanskap digital yang bergejolak? Mari kita lihat tantangannya.
Perhatian Pada HAM Bisa Menguntungkan
Indonesia, sebagai salah satu raksasa digital dengan populasi pengguna internet dan media sosial yang masif, jelas membutuhkan fondasi tata kelola platform yang kokoh. Dalam konteks ini, perhatian UNESCO pada kebebasan berekspresi dan HAM, adalah angin segar.
Di tengah hiruk-pikuk perdebatan hoaks dan potensi pembatasan ekspresi, prinsip-prinsip HAM internasional dapat menjadi jangkar yang esensial, memastikan regulasi tidak membungkam suara kritis atau memangkas akses informasi yang sah.
Pendekatan multipihak yang diusung UNESCO—melibatkan pemerintah, platform, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas teknis—adalah keniscayaan yang telah lama dinanti di Indonesia.
Selama ini, formulasi regulasi kerap didominasi satu pihak, menghasilkan kebijakan yang bias. Kolaborasi dibutuhkan agar terbuka ruang dialog yang inklusif, menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif bagi ekosistem digital yang terus berevolusi.
Sementara, kewajiban platform untuk melakukan uji tuntas HAM dan meningkatkan transparansi operasional adalah langkah maju. Ini menjawab kekhawatiran publik di Indonesia mengenai moderasi konten, terutama terkait isu sensitif seperti SARA.
Transparansi yang lebih mendalam akan menumbuhkan kepercayaan publik dan membuka jalan bagi akuntabilitas yang lebih substansial dari para raksasa digital.
Peningkatan melek media dan informasi (MIL), sebagaimana ditekankan pedoman UNESCO, adalah kebutuhan mendesak untuk memerangi gelombang disinformasi dan ujaran kebencian. Perlu implementasi program edukasi yang terstruktur dan komprehensif.
Lebih lanjut, perhatian khusus UNESCO terhadap perlindungan kelompok rentan—perempuan, anak-anak, jurnalis, seniman, dan pembela HAM—adalah krusial, mengingat mereka seringkali menjadi sasaran empuk kekerasan daring dan disinformasi di Indonesia.
Di balik potensi yang cerah, implementasi pedoman UNESCO di Indonesia terbentur pada realitas yang kompleks. Tantangan utama terletak pada interpretasi dan penegakan prinsip-prinsip HAM internasional dalam bingkai hukum dan budaya Indonesia.
Regulasi yang ada, seperti UU ITE, masih menyisakan pasal-pasal karet yang rentan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi, mengikis konsistensi dengan Pasal 19 (3) dan 20 ICCPR yang diusung UNESCO.
Lanskap Terjal Tata Kelola Indonesia
Tantangan pertama adalah independensi regulator. Pedoman UNESCO menekankan pentingnya regulator yang bebas dari intervensi politik dan ekonomi. Di Indonesia, independensi lembaga regulator seringkali dipertanyakan.
Membangun regulator yang benar-benar mandiri, dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai, adalah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi. Regulator ibarat wasit yang harus siap meniup peluit setiap kali ada pelanggaran.
Isu ini penting, mengingat intervensi pemerintah dalam permintaan penurunan/pemblokiran konten, terkadang kurang transparan, berpotensi menjadi alat sensor, membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat.
Di sisi lain kapasitas dan sumber daya untuk implementasi uji tuntas HAM, moderasi konten multibahasa, dan mekanisme pelaporan yang efektif membutuhkan investasi kolosal. Platform global mungkin mampu, namun platform lokal atau startup bisa jadi tercekik.
Ditambah lagi kesenjangan digital di tingkat masyarakat sebagai pengguna yang masih membentang di berbagai daerah. Ini akan menghambat upaya melek media yang merata dan akses yang setara terhadap informasi.
Inilah alasan pedoman UNESCO menuntut moderasi konten yang peka terhadap nuansa bahasa dan budaya setempat, sebuah tugas raksasa bagi platform. Tuntutan ini berhadapan dengan bahasa dan konteks lokal Indonesia, dengan ratusan bahasa daerah.
Terakhir, isu monetisasi konten berbahaya—termasuk disinformasi dan ujaran kebencian—yang bisa viral dan menguntungkan penyebarnya, harus ditangani dengan serius. Diperlukan upaya terpadu dari platform dan regulator untuk memutus mata rantai monetisasi ini.
Pedoman Tata Kelola Platform Digital UNESCO adalah kompas vital menuju ekosistem digital yang lebih sehat dan berpusat pada manusia. Di Indonesia, pedoman ini relevan sebagai panduan memperkuat kerangka regulasi dan mengembangkan kebijakan yang inklusif dan berorientasi HAM.
Namun, implementasi yang efektif hanya akan terwujud melalui komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, keberanian untuk mengatasi tantangan hukum, independensi regulator, peningkatan kapasitas, dan kepekaan terhadap konteks lokal.
Hanya dengan kolaborasi yang tulus dan penegakan prinsip-prinsip HAM yang konsisten, Indonesia dapat meraih potensi penuh dari pedoman ini, membangun ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi seluruh warganya.
*Photo by Roberto Nickson from Pexels